Ursula Florene
Sudah 7 tahun berlalu sejak pengungsi etnis Rohingya mendarat di Indonesia. Mereka melarikan diri dari konflik berdarah di negara asal mereka, Myanmar, entah sekedar untuk transit ataupun berharap mendapatkan suaka.
Waktu yang lama tidak lantas membuat Indonesia siap dengan sumber daya maupun regulasi yang memadai bagi pengungsi. “Indonesia memang mempunyai jaminan normatif yang menjadi pedoman para pejabat di lapangan dalam menangani pengungsi Rohingya,” kata Peneliti SUAKA Rizka Argadianti saat memaparkan hasil penelitian bertajuk “Hidup yang Terabaikan” di Jakarta pada Senin, 5 Desember 2016.
Sepanjang Juni hingga Oktober 2016, SUAKA melakukan penelitian terkait kondisi para pengungsi Rohingya di Indonesia. Lokasinya tersebar di 4 lokasi dengan jumlah pengungsi terbesar yakni Aceh, Makassar, Medan, dan Jakarta. Total, ada 959 pengungsi Rohingya yang bertahan di Indonesia.
Hasilnya, mereka menemukan adanya masalah pada hak-hak dasar kemanusiaan pengungsi, terutama anak-anak. Hak tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, sipil, dan hukum.
Masalah pendidikan
Ratusan anak Rohingya yang berada di Indonesia kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Menurut Rizka, memang ada sekolah negeri setempat yang bersedia untuk dititipi anak-anak tersebut.
“Tetapi memang soal pendidikan ini tidak merata, karena kalau di kota selain Aceh, ada yang bisa sampai universitas. Tapi di Aceh hanya pendidikan dasar saja,” kata Rizka.
Ia sendiri tidak tahu jumlah pasti anak-anak tersebut karena lokasinya tersebar. namun, mereka berada di rentang usia bayi baru lahir hingga 18 tahun.
Meski ada yang bisa mengikuti pendidikan hingga tuntas, namun hal tersebut tidak diakui secara formal. Anak-anak ini tidak mendapatkan ijazah sehingga tidak ada bukti sah kalau mereka telah menuntaskan pendidikan di Indonesia.
Masalah kesehatan
Para pengungsi juga terbatas akses terhadap kesehatan, seperti misalkan mendapat layanan. Salah satu yang menjadi contoh adalah saat proses persalinan.
“Mereka saat mau melahirkan bisa dioper kesana kemari atau tidak kunjung mendapatkan bantuan karena pengurusan izin yang sulit. Seperti misalkan harus memberitahu IOM, UNHCR, dan lain-lain,” kata Koordinator Kampanye SUAKA Zico Efraindio Pestalozzi yang juga terlibat dalam penelitian ini.
Mendapat pekerjaan
Salah satu kendala lainnya adalah, karena mereka berstatus sebagai pengungsi, maka tidak dibolehkan untuk bekerja di Indonesia. Maka di kamp pengungsi maupun shelter para warga Rohingya ini tidak bisa mencari uang.
Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi 1951 sehingga tidak berkewajiban untuk menyediakan lapangan kerja bagi pengungsi.
Mereka sepenuhnya bergantung pada tunjangan dari International Organization for Migration (IMO). Sayangnya, hal ini justru malah menimbulkan konflik dan rasa iri pada masyarakat lokal setempat.
“Seperti di Aceh, masyarakat sekitarnya malah bertanya-tanya kenapa pengungsi yang tidak ngapa-ngapain dapat gaji. Padahal itu kan tunjangan,” kata dia.
Selain itu, banyak pula yang akhirnya menjadi pekerja ilegal. Seperti membantu nelayan lokal, yang upahnya digunakan untuk membeli baju dan pulsa telepon.
Hak untuk berkeluarga
Selain itu, banyak terjadi perkawinan campur antara pengungsi dengan masyarakat di sekitarnya. Sayangnya, perkawinan ini tidak tercatat karena hukum sipil tidak mengenal perkawinan campur dengan pengungsi. “Jadi tidak dicatat dalam administrasi perkawinan,” kata Zico.
Ada pula kasus di Makassar, yang justru petugas Kantor Urusan Agama malah mengeluarkan buku nikah. “Petugas imigrasi sampai harus mendekati KUA yang bersangkutan dan menjelaskan tentang pengungsi dan pencari suaka,” kata dia.
Perkawinan antar pengungsi juga sama. Tidak ada mekanisme pencatatan sipil untuk mereka, yang tentunya berdampak pada anak-anak yang lahir.
Pengungsi di mata hukum
Bila ada konflik yang melibatkan pengungsi, biasanya yang turun tangan secara langsung adalah imigrasi. Namun, peneliti menemukan bila pengungsi yang menjadi korban, justru mereka tidak melapor.
“Karena nanti takut ditahan di rumah detensi imigrasi, atau dipindah ke tempat lain,” kata Rizka. Maka, bila antar pengungsi ataupun dengan warga lokal ada masalah, kebanyakan mereka selesaikan sendiri.
Apa yang harus dilakukan?
Mantan Protective Officer UNHCR Enny Soeprapto mengatakan, sejarah pengungsi di Indonesia bukan baru Rohingya saja. Sejak zaman kemerdekaan, sudah ada tentara desersi dari Inggris, pengungsi dari Vietnam, hingga pengungsi perang Afghanistan.
Saat ini, ada 13.851 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Mereka berasal dari Afghanistan, Somalia, dan Myanmar. Khusus Rohingya sendiri, ada sebanyak 959 orang, termasuk 67 pencari suaka.
“Tetapi belum ada satu kebijakan, atau regulasi, yang spesifik mengatur soal pengungsi ini,” kata dia. Memang sudah ada UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, namun belum sampai detail.
Dalam UU tersebut, dituliskan kalau ‘kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dan yang pokok-pokoknya hendaknya diatur dengan Keputusan Presiden.’
Sayang, hingga saat ini produk hukum yang disebutkan belum juga lahir. “Bahkan influx pengungsi Rohingya pada 2015 lalu tidak juga mendorong presiden untuk meneken Perpres,” kata Rizka menambahkan.
Menurut Enny, pemerintah terlihat seolah tidak mau pusing menangani persoalan pengungsi sehingga menyerahkan semuanya pada lembaga eksternal. Faktanya, ketiadaan payung hukum ini justru menciptakan diskresi sektoral yang rawan bentrok ataupun dasar hukum.
Padahal, Indonesia adalah salah satu negara yang banyak dituju oleh pengungsi. Entah hanya untuk transit sebelum mendapat suaka di negara lain, ataupun memang mereka ingin mendapatkan perlindungan di sini.
Masalah baru muncul jika negara yang hendak dituju tak mau menerima mereka, sedangkan para pengungsi ini juga menolak jika harus dipulangkan.
Bila pemerintah meneken kebijakan soal pengungsi ini, Enny menilai akhirnya krisis pengungsi tersebut dilihat dari sudut pandang kemanusiaan. “Selama masih dari keamanan dan imigrasi, maka tak akan pernah terlaksana,” kata dia. Indonesia, kata dia, harus mengubah persepsi dalam menangani pengungsi dan pencari suaka.
Enny mencontohkan Malaysia, yang secara kepadatan penduduk hingga luas daerah tentu tak berbanding dengan Indonesia. Tetapi mereka bersedia meratifikasi Konvensi 1951 dan menampung pengungsi Rohingya.
Ia melihat keberadaan pengungsi tidak lantas menjadi momok bagi warga asli. Seperti misalkan, lapangan pekerjaan.
“Apakah 3 ribu pengungsi yang ada di usia kerja lantas merebut lapangan kerja Indonesia? Kan tidak. Kalau mereka bekerja dan tidak membebani siapapun untuk hidup, kan malah menggerakkan perekonomian negara,” kata dia.
Namun, hingga saat ini belum ada niatan dari pemerintah untuk menyatakan hal tersebut. Para pengungsi Rohingya masih menjadi anak tiri di negeri sendiri, maupun di Indonesia.—Rappler.com
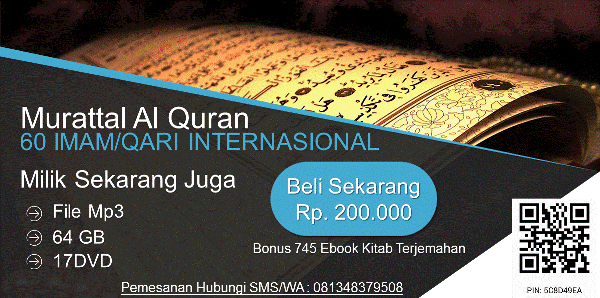


0 komentar:
Post a Comment