oleh : Wahyudi Abdurrahim, Lc (PCI Muhammadiyah Mesir)
Fatwa terkait erat dengan hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Fatwa juga erat hubungannya dengan berbagai kejadian terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Ulama ushul fikih sering menyebutnya dengan ahkamu annawazil, yaitu persoalan-persoalan baru yang belum pernah ada dalam suatu masyarakat. Ahkamunnawazil ini kadang sangat kondisional dan temporal. Ia bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
Dalam mengeluarkan fatwa, ada syarat yang harus dipenuih oleh seorang mufti, di antaranya adalah
- Mengetahui al-Quran dan sunnah serta berbagai cabang ilmu yang terkait dengan keduanya.
- Mengetahui ijmak ulama serta berbagai persoalan yang menjadi khilaf di kalangan para ulama.
- Mengetahui secara mendalam metodologi ijtihad (ilmu ushul fikih)
- Memahami persoalan yang sedang terjadi secara mendalam.
- Mengetahui kondisi suatu masyarakat, termasuk tradisi yang sedang berkembang saat ini.
- Mampu menggali hukum syariat dari nas baik al-Quran maupun sunnah.
- Menanyakan persoalan kepada pakar tertentu di bidangnya jika suatu persoalan bukan menjadi spesialisasinya.
الحكم علي شيئ جزء من تصوره
Maksudnya adalah bahwa dalam memberikan ketetapan hukum, sangat bergantung terhadap pemahaman seseorang atas suatu persoalan. Kesalahan dalam mengeluarkan fatwa, bisa jadi disebabkan oleh kesalahpahaman mufti terhadap suatu persoalan yang sedang dihadapi oleh seseorang. Oleh karena itu, seorang mufti sebelum mengeluarkan fatwa, akan melihat secara obyektif suatu persoalan suatu masyarakat.
Tentu saja kadar persoalan berbeda dari suatu kasus ke kasus yang lain, dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Jika kasusnya terkait dengan penistaan agama yang menggunakan bahasa Indonesia, maka yang lebih paham terhadap persoanan ini tentu para pakar dibidangnya, yaitu para pakar bahasa Indonesia atau orang-orang yang setiap hari berbicara dengan bahasa Indonesia secara natural. Mereka ini yang lebih berhak untuk menjadi saksi ahli atas kasus penistaan agama yang disebabkan oleh penggunaan bahasa Indonesia.
Suatu kesalahan fatal jika kasus penistaan agama yang menggunakan bahasa Indonesia, lalu mendatangkan saksi ahli dari masyayih kubar yang berasal dari negara lain yang tidak mengerti mengenai seluk beluk bahasa Indonesia. Mufti tadi, dalam memahami nas, pada akhirnya sangat bergantung kepada orang yang menerjemahkan dan memberikan masukan. Jadi, fatwa yang akan dikeluarkan, menjadi bias.
Kecuali jika seorang mufti tadi, karena ketidakmampuan atas suatu bahasa, maka ia mendatangkan para pakar bahasa Indonesia secara terbuka, seperti yang tercantum dalam syarat nomor tujuh. Ia boleh mengeluarkan fatwa setelah mendengarkan ungkapan para pakar bahasa dengan melihat pada persoalan secara berimbang. Jika tidak dan hanya mengandalkan pada masukan sepihak, fatwa yang akan dikeluarkan juga akan berpihak tanpa disadari oleh sang mufti.
Selain mengetahui persoalan, seorang mufti juga harus mengetahui kondisi sosial suatu masyarakat. Perubahan tradisi dan kondisi suatu masyarakat, dapat merubah fatwa, meski persoalan yang dihadapi sama. Contoh rilnya adalah ketika Dar Ifta ditanya mengenai pemilihan pemimpin non muslim dari penanya yang tinggal di Amerika atau Eropa Barat. Orang muslim di sana minoritas. Para calon kandidat tidak ada yang muslim. Dari kondisi seperti ini, muncullah fatwa bahwa seorang muslim boleh memilih pemimpin non muslim. Tentu saja dengan melihat kaedah:
ارتكاب اخف الضررين واهون الشريرين
Melakukan perbuatan yang mengandung mudarat dan keburukan paling kecil.
Artinya, jika ada dua kandidat non muslim, hendaknya para minoritas itu memilih pemimpin yang kiranya mudaratnya bagi umat Islam lebih kecil dibandingkan dengan calon pemimpin yang mudaratnya lebih besar. Atau hendaknya mereka ikut aktif memilih dibandingkan mereka tidak pergi ke tempat pemilihan yang dapat berimplikasi pada kemenangan kandidat yang membahayakan umat Islam.
Sebuah kesalahan fatal jika kemudian fatwa Dar Ifta ini di bawa ke Indonesia dengan justifikasi bahwa Dar Ifta Mesir saja membolehkan pemilihan non muslim. Umat Islam Indonesia bukanlah umat minoritas. Para calon kandidat pun tidak semuanya non muslim, namun tetap ada yang muslim. Jika fatwa yang ditujukan kepada kaum minoritas dibawa ke umat mayoritas seperti Indonesia, maka yang terjadi adalah bencana.
Contoh lain, terkait pelecehan agama yang terjadi di tanah air. Tentu yang mengerti dan paham terkait masalah ini adalah masyarakat Indonesia. Umat Islam Indonesia yang memahami konteks, kapan dan di mana ungkapan pennistaan disampaikan. Mereka juga yang lebih tau mengenai karakter dan tipe orang yang melakukan penistaan. Jika dalam kasus ini, kemudian memanggil mufti dari luar, sang mufti bias jadi mengeluarkan fatwa yang keliru. Hal ini mengingat budaya di mana sang mufti tinggal dengan kronologi kejadian yang sedang terjadi di Indonesia, sangat berbeda. Pemahaman keliru, akan berakibat kepada fatwa yang keliru juga.
Tidak heran jika dalam sejarah, Imam Syafii mempunyai Qaul Qadim di Bagdad dengan Qual Jadid di Mesir. Salah satu faktor yang melatarbelakangi perbedaan fatwa tersebut, adalah karena perbedaan kondisi sosial antara masyarakat Mesir dengan Bagdad. Kondisi sosial ini berimplikasi pada perbedaan fatwa yang dikeluarkan.
Mengapa kondisi sosial menjadi pertimbangan? Karena kondisi sosial menyangkut maslahat. Fatwa harus berpjak pada sisi maslahat. Bisa saja suatu persoalan maslahat dan cocok di suatu daerah, namun sebaliknya mengandung mudarat dan menimbulkan fitnah besar bagi daerah dan negeri lain. Oleh karena itu, para ulama meletakkan banyak kaedah, di antaranya seperti yang dinyatakan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab I’lamul Muwaqqiin berikut ini:
تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد
Artinya: Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat
Perubahan fatawa tidak dianggap menyalahi hukum syariat. Bahkan perubahan itu merupakan tuntunan syariat. Hal itu karena hukum syariat selalu melihat maslahat hamba, seperti pernyataan Ibnul Qayyim dalam kitab I’lamul Muwaqqiin mengatakan, “Landasan dan pondasi hukum syariat adalah maslahat hamba baik di dunia maupun di akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya rahmah, semuanya mengandung maslahat, dan semuanya mengandung hikmah. Semua persoalan yang keluar dari jalur keadilan menuju kezhaliman, dari rahmah kepada sebaliknya, dari maslahat menuju mafsadat, dan dari hikmah menuju kesia-siaan, maka itu bukan lagi bagian dari syariat, meski itu sudah ditakwil”.
Oleh karenanya, para ulama juga meletakkan kaedah berikut ini:
العادة محكمة
Maksudnya bahwa tradisi menjadi timbangan hukum.
Juga kaedah berikut:
المعروف عرفا كالمشروط شرطا
Maksudnya, suatu tradisi baik yang telah terpaku di masyarakat dan tidak menyalahi syariat Islam, maka ia bagai sebuah syarat.
Pengetahuan suatu tatanan masyarakat, juga terkit erat dengan upaya untuk menutup mafsadat yang merupakan kewajiban bagi hukum syariat. Iz Ibnu Abdussalam dalam kitab Qawaidul Ahkam berkata, “Mendahulukan maslahat yang kemungkinan besar akan didapatkan dari mafsadah yang kemungkinan kecil akan muncul merupakan perbuatan baik yang terpuji. Menutup mafsadah yang kemungkinan besar akan muncul, dari maslahat yang kemungkinan kecil akan muncul itu perbuatan baik dan terpuji”
Terkait upaya menutup mafsadat ini, ulama ushul meletakkan kaedah berikut ini:
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
Menangkal mafsadah harus didahulukan daripada untuk mendapatkan suatu maslahat.
Sebagaimana keterangan di atas, bahwa seorang mufti harus menguasai persoalan yang sedang terjadi di suatu masyarakat dan juga mengetahui mengenai tradisi masyarakat tempatan. Secara umum, yang lebih mengetahui terkait dengan dua hal tersebut adalah para ulama yang tinggal di wilayah itu dan bukan ulama yang tinggal di wilayah lain. Oleh karena itu, Imam Qarrafi dengan tegas mengatakan bahwa seorang mufti dilarang mengeluarkan fatwa diluar tradisi yang berkembang di suatu masyarakat. Lebih tegas Imam Qarrafi mengatakan bahwa selayaknya suatu masyarakat menanyakan persoalan kepada ulama di daerahnya dan bukan kepada ulama di daerah lain.
Untuk kasus di Indonesia, tentu saja yang lebih mengerti mengenai persoalan penistaan agama yang sedang terjadi, adalah para ulama Indonesia, dan bukan ulama Timur Tengah. Ulama Indonesia, diwadahi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi persoalan keumatan tadi, seyogyanya dirujuk kepada MUI, dan bukan menanyakan dan meminta fatwa dari ulama Timur Tengah.
Akan fatal akibatnya jika MUI sebagai representatif ulama Indonesia dilangkahi dan tidak dianggap sama sekali, lalu mencari pembenaran dengan menanyakan atau mengundang mufti dari lembaga fatwa di luar Indonesia. Melangkahi MUI, selain menyalahi prosedur fatwa, juga merupakan sikap arogansi dan terkesan merendahkan MUI. Sikap seperti ini bisa berakibat fatal karena akan membenturkan antar lembaga fatwa dunia. Maka yang terjadi di masyarakat adalah kekisruhan. Fatwa sejatinya untuk mendamaikan dan solusi atas persoalan umat sesuai dengan maslahat mereka, dan bukan menjadi upaya pemecah belah umat. Jika fatwa berdampak pada sikap umat yang saling curiga, hasad, saling menyalahkan, saling hujat dan saling cemooh, itu sama artinya dengan sikap adudomba antar sesama umat Islam. Wallahu a’lam
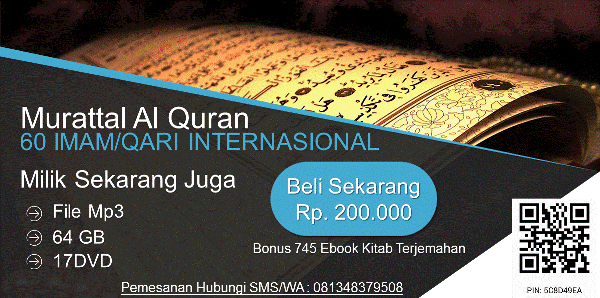


0 komentar:
Post a Comment