Oleh : Rizal amri
Kecendrungan suara perkotaan menunjukkan fenomena yang menarik khususnya pada dua pekan menjelang “Pilpres” . Suara perkotaan umumnya lebih menjagokan Prabowo-Hatta yang mana tercermin dari hasil polling di berbagai media, termasuk di Kompasiana ini.
Padahal popularitas Jokowi melambung setelah beliau masuk kota, menjadi Gubernur DKI Jakarta. Adalah media yang ikut membesarkan Jokowi dan mereka yang melek media umumnya berdomisili di perkotaan. Kota dan kaum melek media identik dengan kalangan yang tingkat pendidikan dan kesejahteraannya relatif lebih baik di banding pedesaan. Kalangan “well educated” ini pula lah yang begitu gencar mengapresiasi gaya kepemimpinan Jokowi, khususnya melalui berbagai media sosial. Masifnya dukungan kalangan medsos dan pemberitaan media, menjadi pemicu dan mengantarkan Jokowi maju di “Pilpres”.
Wajar jika fenomena ini mengejutkan banyak pihak , termasuk Jokowi sendiri sebagaimana pernah beliau ungkapkan. Sebagian pendukung Jokowi bisa jadi melihatnya sebagai sebuah anomali dan fakta yang sulit diterima. Sekalipun secara nasional peluang kedua kandidat masih berimbang, namun lepasnya suara kota tentu kurang menggembirakan bagi kubu Jokowi. Dukungan kota atau kaum terdidik tentu punya nilai prestisius sekalipun bukan jaminan kemenangan.
“Anomali” pemilih berdasarkan disparitas tingkat pendidikan ini terkomfirmasi lagi oleh hasil survey Vox Populli, dimana dukungan bagi Jokowi hanya kuat di kalangan tidak tamat SD.
http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/06/20/1649143/hasil.survei.vox.populi.jokowi.hanya.unggul.pada.pemilih.tidak.tamat
Kagagalan Merasionalitaskan Pilihan
Kepopuleran Jokowi boleh dibilang tidak terlepas dari kepiawaian beliau dalam membuat branding diri, yakni dengan melakukan strategi diferensiasi.
Menjawab pertanyaan seorang mahasiswa tentang cara membuat branding untuk diri sebagai pemimpin, Jokowi dengan lugas mengatakan bahwa orang yang bergerak di bidang politik harus bisa membentuk diferensiasi diri. “Kalau sama saja ya masyarakat juga enggak tertarik dong,” katanya. Prinsip itu, kata dia, didapat setelah bergelut di bidang wirausaha selama 23 tahun. “Percuma dong 23 tahun di bidang marketing tapi enggak bisa memasarkan diri sendiri,” katanya.
Jokowi memang jagonya trendsetter, berbagai aksi dan atribut yang dikenakan Jokowi selalu saja menarik perhatian publik. Berkat bantuan media, ikon kesederhanaan, kebersahajaan, dan kemerakyatan menyatu dengan Jokowi. Publik hampir tidak bisa membedakan apakah itu natural atau “by design” seperti yang diungkap Jokowi di atas.
Namun dengan berjalannya waktu, ketika media juga terbelah menjadi dua kubu, media rival Jokowi mulai marak mengungkapkan fakta sisi lain dari Jokowi. Jokowi kemudian terkesan sebagai sosok berkepribadian ganda, kadang naik becak di waktu lain carter pesawat, Jokowi tak sungkan memakai baju kemeja berharga seratus ribuan, padahal di waktu yang sama istrinya dikabarkan pakai tas merek Chanel yang berharga puluhan juta rupiah, dll. Kondisi ini tentu membuat pemilih perkotaan mulai merasionalitaskan pilihan. Bangun dari ilusi-ilusi tentang sosok “Nabi baru” ataupun Ratu Adil. Eksploitasi yang berlebihan tentang kesederhanaan Jokowi malah membuat jenuh masyarakat dan menjadi bumerang.
Timses Jokowi bukannya tidak menyadari hal ini. Mereka sudah berupaya merasionalitaskan alasan untuk memilih Jokowi.
Adalah Anis Baswedan yang mencoba membuat diferensiasi dengan mengidentikkan Jokowi dan kubunya sebagai kelompok “orang baik-baik” dan kubu di seberang dengan kategori sebaliknya. Namun hal itu belum cukup untuk “menyetrum” rasionalitas pemilih. Jika kubu Prabowo dituding sebagai bukan kelompok orang baik, misalnya merujuk pada tudingan pelanggaran HAM, bukankah di kubu Jokowi juga terdapat sederetan nama yang punya sejarah kelam menyangkut HAM. Jika tudingan itu terkait dengan kasus korupsi sejumlah petinggi partai di kubu Prabowo, bukankah partai di pihak Jokowi, terutama PDIP adalah teratas dalam jeratan perkara korupsi. Boni Hargens pendukung Jokowi lainnya, juga mencoba membuat diferensiasi dengan menyebut Jokowi membawa bangsa ke “masa depan”, sedangan kubu seberang menuju masa lalu. Argumen Boni ini layu dengan sendirinya mengingat Jusuf Kalla cawapres Jokowi adalah orang masa lalu. Boni tentu menyadari betul hal ini, mengingat beliau adalah salah seorang yang sangat menolak JK menjadi cawapres Jokowi.
Rasionalitas pemilih kalangan terdidik tidaklah terbentuk melalui doktrinasi, mereka punya logika sendiri yang bersifat variatif tergantung latar belakangnya. Debat dua kali capres kemaren, telah menjadi salah satu faktor penentu preferensi mereka. “Isi kepala” capres bisa membangunkan sebagian mereka dari ilusi dan membangkitkan rasionalitas. Mereka yang paham ilmu manajemen tentu sepakat bahwa Jokowi bagus untuk kelas menejer dan Prabowo lebih pantas sebagai leader. Adapun kaum pebisnis dan mereka yang suka main di bursa punya logika yang lain lagi. Prabowo yang punya karakter tegas, dengan dukungan mayoritas di parlemen tentu akan memerintah lebih efektif dan diyakini lebih mampu menjaga stabilitas yang menjadi modal dasar keberlangsungan perekonomian.
Jokowi dan Timses tampaknya perlu berpikir lebih keras untuk merasionalitaskan pilihan demi merebut kembali suara pemilih kota. Perlu juga ditertibkan komponen-komponen timses yang melakukan serangan-serangan yang bernuasa kepanikan, seperti Wimar Witoelar yang melepaskan peluru secara membabi buta sehingga mengentalkan kesan islamophobia di lingkungan Jokowi.
Di sisi lain, koalisi ramping di kubu Jokowi tampaknya masih kurang runcing. Suara desa yang sebagian besar dikuasai Golkar, tentu tidak mudah untuk dipenetrasi oleh partai yang sebarannya kurang merata seperti PKB dan partai-partai baru seperti Nasdem.
Koalisi ramping bisa jadi sebuah kebijakan yang keliru dari Megawati, mengingat daya magnet Jokowi tidaklah sebagaimana SBY di dua kali pilpres yang lalu. Megawati boleh jadi menyesal telah menawarkan harga yang tidak mungkin diterima Golkar, hal mana bisa membawanya pada “mimpi buruk” pilpres 1999, yakni PDIP memenangi pemilu tapi kalah di pilpres.
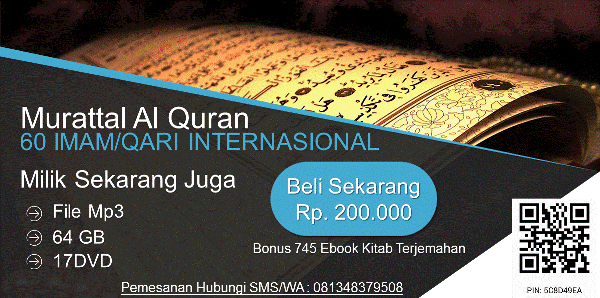






0 komentar:
Post a Comment