Lembaga Fund of Peace menempatkan Indonesia berdiri pada posisi ke 87 dari daftar negara yang paling rentan di dunia. Kerentanan Indonesia untuk menjadi negara gagal memang belum pada level yang mengkhawatirkan. Paling tidak ukurannya hingga 2015.
Namun jika mencermati data yang disajikan oleh lembaga non profit asal Washington itu, ada sisi yang benar-benar kita mesti cermati. Sebab sejak 2014, grafik Indonesia untuk menjauhi label negara gagal terus berkurang. Pada tahun 2011, Indonesia mencatat 6,7 poin menjauhi label negara gagal. Takaran angka ini terbilang sangat singnifikan.
Pada tahun 2012 dan 2013, poin pertumbuhan yang dicatat Indonesia pun masih cukup baik 5,7 dan 3,3 poin menjauhi label negara gagal. Namun sejak suksesi pemerintahan dari SBY ke Jokowi, poin pertumbuhannya jauh berkurang.
Memang, poin Indonesia masih positif. Namun angka pertumbuhannya hanya 1,9. Angka yang jauh lebih kecil terjadi di 2015 yang mana kini angka pertumbuhan Indonesia menjauhi label negara gagal hanya 0,1 poin.
Banyak faktor untuk mengukur tingkat kegagalan sebuah negara. Faktor itu di antaranya sosial, ekonomi, dan politik.
Namun untuk bahasan kali ini, saya akan fokus membedah faktor politik yang mengancam sebuah negara terperosok menjadi negara gagal.
Dalam daftar yang dikeluarkan Found of Peace terungkap fakta bahwa negara yang menempati peringkat teratas negara gagal memiliki masalah serius terkait situasi politik nasionalnya.
Somalia yang berada di peringkat pertama, dilanda konflik politik berkepanjangan sejak 1991. Status negara itu masih perang saudara akibat konflik yang tak terselesaikan antara dua kubu. Ini pemicunya adalah kekosongan hukum usai tumbangnya rezim Siad Barre.
Tak adanya supremasi hukum membuat gerilyawan Islam menerapkan hukumnya sendiri di kota kekuasaannya. Sebaliknya militer Somalia punya prinsip hukum yang mengacu pada konstitusi lama peninggalan Barre.
Dan tidak adanya kepastian hukum itulah, perang berkobar tanpa henti, khususnya di Somalia Selatan. Akibatnya, hingga kini negara itu jadi negara yang paling gagal di muka bumi.
Akibat tak adanya supremasi hukum, sejumlah organisasi teroris pun tumbuh subur di negara itu.
Tentu tak ada satu pun orang yang menginginkan situasi di Somalia terjadi di Indonesia. Namun pelajaran di Somalia juga perlu kita cermati. Ini agar bangsa ini mampu menghindari ancaman terperosok menjadi negara gagal.
Sebab, ancaman itu nyata terbentang di hadapan mata. Makin lama kualifikasi pertumbuhan Indonesia sebagai negara berhasil terus terdegradasi. Pertumbuhan yang menurun ini tak terlepas dari momen pada 2014.
Lagi-lagi soal politik menjadi salah satu penyebabnya. Kerasnya pertarungan pada Pilpres 2014 masih membagi Indonesia pada dua kutub politik yang berseberangan. Tajamnya polarisasi politik ini memang sangat berbahaya jika tak diarahkan ke jalur yang benar.
Sebab hal ini bisa menjadi bensin yang memicu potensi Indonesia sebagai negara gagal. Jika bensin ini terpantik percikan api, maka potensi konflik bisa melanda bangsa ini.
Ujian kini ada depan mata bila melihat situasi terkini jelang Pemilukada 2017, khususnya Pemilukada DKI Jakarta.
Ya, polarisasi yang belum selesai usai Pilpres 2014 tambah tajam jelang Pemilukada DKI. Penyebabnya adalah perseteruan pendukung calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan pendukung calon lain.
Memang, kekuatan massa yang pada Pilpres 2014 lalu memilih Jokowi belum pasti memilih Ahok. Tapi hampir dipastikan mayoritas pemilih Ahok memilih Jokowi pasa 2014 lalu.
Sebaliknya, kekuatan oposisi Jokowi kini tersebar di kubu penantang Ahok, baik Anies Baswedan maupun Agus Yudhoyono. Walau begitu, tak sedikit pula pendukung Jokowi yang kini berada di kubu anti-Ahok.
Tajamnya perseteruan politik sejatinya bisa menjadi hal yang sehat. Atau sebaliknya, bisa menghancurkan sama sekali. Tergantung cara mengolahnya. Namun sebuah manuver Ahok yang menyinggung isu SARA bak membuat bensin tersulut api.
Sejak awal, Ahok selalu mengaku jadi korban SARA akibat ada pihak yang menolak dirinya dengan alasan agama. Namun sejatinya sejak awal pula Ahok-lah menarik-narik isu yang berbau agama. Sejak awal menjabat gubernur, Ahok sudah berinvestasi menyinggung isu agama yang berbuah sentimen kelompok tertentu.
Bara yang dipantik Ahok sudah bermula sejak pernyataannya yang menilai pihak yang menolak lokalisasi prostitusi di Jakarta sebagai pihak yang munafik. Padahal motor dari penolakan itu adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah
"Jangan munafik, emang nggak ada prostitusi di DKI? Ngapain munafik? Itu aku nyindir aja," ucap Ahok, 31 Desember 2014. Begitu Ahok yang menegaskan kata 'munafik' hingga dua kali, bagi pihak yang gencar menolak lokalisasi.
Tak hanya itu Ahok pun sempat menyebut jika nabi diturunkan di Jakarta sekalipun tak akan mampu menangani prostitusi. "Bagi saya bukan mempermasalahkan menghilangkan prostitusi di Jakarta. Enggak mungkin. Nabi turun saja enggak bisa menghilangkan loh," kata Ahok di Balai Kota, 27 April 2015.
Belum lagi pernyataan Ahok soal bagaimana penyelenggara event dzikir yang dituding membuat lingkungan Monas menjadi kotor akibat kerap memanfaatkan momen ibadah itu untuk menyewakan lapak bagi PKL. "Saya juga minjamin (Monas) dulu buat zikir, tapi malah orang-orang masuk buat PKL. Enggak bisa dong. Itu EO-nya dapat duit nyewain lapak, saya setengah mati 6-7 bulan beresin!" kata Ahok 19 Oktober 2015.
Memang, ucapan Ahok itu tak sepenuhnya bisa disalahkan. Namun untuk sekelas pemimpin, perkataan yang gegabah malah bisa menimbulkan bibit masalah. Ini terbukti pada ucapan-ucapan Ahok berikutnya.
Ahok pernah menyinggung soal penggunaan jilbab di sekolah. Bahkan seperti dikutip dari Kompas.com edisi 4 Juni 2016, Ahok mengatakan lebih baik serbet di rumahnya dibanding jilbab berukuran besar.
"(Jilbab) yang dipakainya yang kayak serbet. Malah mungkin lebih bagus serbet di dapur saya. Begitu keluar dari sekolah naik motor bapaknya, langsung dibuka," kata Ahok.
Masih banyak lagi perkataan Ahok yang menyinggung isu agama, seperti isu pemotongan hewan kurban. Namun puncak dari semua itu adalah ucapan Ahok yang menyinggung surat Al Maidah Ayat 51. Rentetan tindakan Ahok ini ibarat menyulut api kemarahan sebagian besar kelompok Islam.
Sejatinya rentetan dugaan penistaan agama ini menjadi sebuah rangkaian yang berbeda dengan Pemilukada. Perkataan Ahok pun dinilai tak hanya menjadi isu warga DKI, melainkan isu seluruh Indonesia.
Tak pelak, hal ini membawa implikasi gugatan hukum di seluruh wilayah hukum. Memang tak dipungkiri, mereka yang marah ini secara politis umumnya bukan pemilih Ahok dalam Pemilukada DKI. Namun aksi menolak Ahok kini sudah jauh melenceng dari sekadar persoalan kontestasi politik.
Sebab warga di Naggroe Aceh Darussalam saja sudah ikut bergerak. Mereka menuntut Jakarta segera menyelesaikan proses hukum terhadap sang gubernur. Jika tidak, mereka menuntut Ahok diadili secara hukum Aceh. Sebab Ahok dinilai telah mencederai syariat Islam yang menjadi hukum di daerah itu.
Tak pelak polarisasi makin kental. Dari isu politis menjadi isu yang jauh lebih besar menyangkut kepercayaan serta toleransi berbangsa dan bernegara.
Namun respons hukum terhadap Ahok yang berbelit makin membuat sebagian kelompok mulai jengah. Terlebih ada beberapa pernyataan dari aparat yang menyatakan calon yang akan maju dalam pemilukada tak bisa diproses hukum. Ada pula perkataan yang menyatakan proses hukum Ahok harus seizin Jokowi.
Sekilas, logika ini benar-benar mencederai akal sehat. Jika logika itu dipakai, seorang calon yang maju pemilukada yang diduga membunuh sekalipun tak bisa diproses hukum. Padahal prinsip 'equality under the law' selalu didengungkan sebagai prinsip hukum universal yang bangsa ini anut.
Di sisi lain, pernyataan itu juga berarti menyimpulkan sejak awal bahwa kasus Ahok dan politik adalah rangkaian yang terkait. Padahal bukti yang tersaji begitu jelas tersebar lewat video. Ini bukannya kasus black campaign politik yang penuh fitnah dan rekayasa. Ini adalah kasus yang nyata di depan mata.
Momen ucapan Ahok pun bukan bertepatan dengan agenda politik, melainkan agenda kerjanya sebagai gubernur. Secara gamblang kasus Ahok ini sangat bisa dicerna logika dan akal sehat manusia. Ini adalah perkataan pejabat publik yang mencederai toleransi dan harmoni beragama.
Padahal sisi yang lain, sudah ada sebuah yurispridensi terkait kasus penistaan sebuah ajaran agama. Adalah seorang ibu di Bali, Rusgiani (44 tahun), yang harus dipenjara 14 bulan karena menghina agama Hindu pada 2012.
Hanya beberapa pekan setelah dilaporkan, Rusgiani langsung ditetapkan sebagai tersangka. Namun untuk Ahok, kasusnya hingga kini belum menunjukkan perkembangan hukum yang berarti.
Karena itu, anggapan yang menyatakan calon Ahok tidak bisa diproses hukum karena sedang mengikuti Pemilukada adalah sebuah ucapan yang berbahaya sekaligus gegabah. Ucapan yang bisa melunturkan kepercayaan sebagian kelompok masyarakat terhadap supremasi hukum di negeri ini.
Jika kemudian sebagian rakyat tak tercaya lagi dengan supremasi hukum, ancaman seperti Somalia terbentang di depan mata. Rakyat jadi berani main hakim sendiri. Tentu hal ini harus kita hindari secara bersama. Hukum harus tetap kita junjung tinggi walau langit runtuh.
Semua pihak pun harus memiliki kepala dingin terkait segala polemik yang terjadi terkait Ahok. Pun halnya aparatur pemerintah yang harus adil dalam menegakkan hukum. Jangan hukum tajam kepada rakyat kecil dan musuh politik.
Di sisi lain, hukum kepada rekan koalisi dan konglomerat jadi begitu tumpul. Jika hal itu yang terjadi maka kemarahan rakyat yang bisa menjadi bayarannya. Tentu kita tak ingin kemarahan rakyat kembali terjadi di negeri ini.
Cukuplah momen 1965 dan 1998 menjadi catatan kelam terakhir yang terjadi di tanah air tercinta. Kita tentu tak ingin Indonesia kembali jatuh menjadi negara gagal. Sebab para pendiri bangsa kita telah mewariskan negara ini dengan sebuah tujuan mulia, yakni 'mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.'
Kata adil yang tentu tak hanya ditujukan bagi konglomerat tapi seluruh rakyat. Adil yang bukan hanya untuk pejabat namun seluruh umat.
Mengakhiri tulisan ini, izinkan saya mengutip pernyataan Thomas Jefferson, "When injustice becomes law resistance becomes duty."
Oleh Abdullah Sammy, Jurnalis Republika
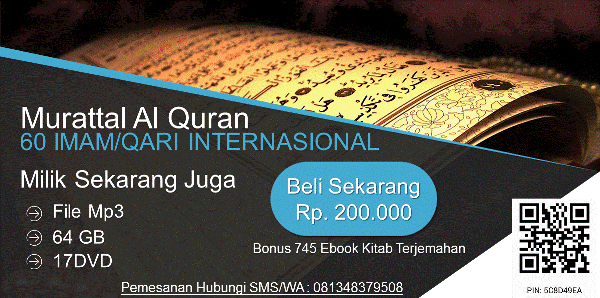






0 komentar:
Post a Comment