Tiga tahun lalu, pukul 6 pagi, baterai telpon selularku tinggal 17 persen, dan malam itu aku tidak tidur.
Dalam beberapa jam kemudian, aku menelpon ke saudaraku dan menjadi panggilan telpon terakhirku sebelum kemudian menyaksikan ‘pembunuhan terburuk dalam sejarah modern atas para peserta aksi protes damai dalam sehari’.
Hari itu adalah 14 Agustus 2013, dan dua bulan lagi, Mesir akan masuk masa libur tahunan. Saya dan teman-teman menyaksikan kudeta militer lewat TV sebulan lalu. Kami ikut aksi duduk di lapangan Rabaa untuk mendukung tuntutan dihormatinya demokrasi. Ribuan orang juga berkumpul disana.
Pagi itu, saya meninggalkan Amir dan Saleh yang masih tertidur di tenda, menuju kedai kopi dekat Tiba Mall yang menjadi tempat bercengkerama selama aksi. Disana, saya bertemu dengan Mohammed, yang membawa serta kameranya. Dia tinggal dekat lapangan Rabaa, sehingga dia sering di malam harinya pulang ke rumah. Namun di malam itu, dia memutuskan tetap bertahan di Rabaa.
Ketika matahari masuk sepenggalah di hari ke 47 aksi protes, aku menyaksikan hal-hal yang janggal.
Di seberang jalan, aku melihat tentara memasang kawat berduri di depan markas tentara, memagari dari atas hingga bawah, padahal tidak ada serangan atas gedung mereka selama aksi protes berlangsung.
Berikutnya, aku memperhatikan di atas gedung, beberapa karung pasir ditumpuk beberapa meter, menghadap kearah para pengunjuk rasa.
Bateraiku mau habis, aku mencari tempat untuk mengisinya, namun saluran listrik ternyata telah diputus. Saat itu, aku mulai menyadari bahwa akan ada hal-hal buruk yang terjadi. Aku tidak lagi berpikir tentang selulerku. Aku kembali ke kedai kopi, bergantian melihat ke atap bangunan markas tentara dan tenda para pengunjuk rasa di bawahnya. Terlihat tentara mengarahkan senjatanya ke arah kerumunan dan sejenak bersembunyi di balik tumpukan karung pasir. “Apa kamu lihat?,” tanya pemilik kedai kopi keheranan. Disaat itulah, saya mulai paham apa yang akan terjadi dan segera mengirim pesan ke teman-teman lewat seluler.
Waktu menunjukkan pukul 7.30 pagi. Aku bergegas meninggalkan kedai dan memutuskan melihat apa yang terjadi di belakang Tiba Mall di Jalan Anwar Al-Mofti. Ternyata ada yang ganjil, jalanan lengang.
Dari belakang, aku melihat seorang pria dengan menggendong anak kecil berlarian di belakangku. Aku berpaling dan jantungku seperti berhenti berdetak.
Mobil Humvee polisi muncul dari sisi jalan, kebanyakannya tidak kelihatan karena terhalang tumpukan karung pasir yang menjadi pintu masuk dan keluar para pendemo. Aku tidak pernah melihat polisi menggunakan kendaraan itu sebelumnya, dan mereka kini berada 20 meter dari tempatku berdiri.
Bayangan dalam benakku tidak karuan, saya tidak bisa konsentrasi lagi hingga kemudian terdengar teriakan, “Lari Mahmoud..Lari…”
Ketika saya bersiap berlari, gas air mata telah ditembakkan dan jatuh beberapa meter di samping saya.
Aku kembali ke tenda dan ternyata orang-orang sudah bangun. Ada kepanikan terjadi. Beberapa orang tergesa-gesa menelpon teman atau kerabatnya untuk memberitahu apa yang tengah terjadi.
Penembak jitu dan aparat keamanan dari atap markas militer mulai menembaki kerumunan. Pada saat itu, instingku bekerja. “Lari…”, teriakku dalam hati. Orang-orang juga berlarian menyelamatkan diri, ketika gas air mata menghujani mereka. Suasanapun menjadi kacau balau.
Aku dan temanku kemudian berhenti. Kami menutupi wajah kami agar tidak menghirup gas air mata. Aktivitas online-ku selama aksi protes telah mengajariku bagaimana menghadapi gas air mata, tutup wajah dan masukkan kaleng gas itu ke air. Para pendemo kemudian mencari ember dan diisi air dari kran di dekat kedai kopi.
Ketika bebeberapa tempat mulai kosong karena gas air mata, tiba-tiba kami terkejut karena seorang yang berdiri beberapa meter di sampingku jatuh tersungkur, tidak bergerak. Tidak ada waktu untuk mengetahui apa yang terjadi. Kami mengangkatnya dan membawanya ke El Nasr, jalan utama, dimana kami bertemu dengan banyak orang yang mengendarai motor sambil mengangkut orang-orang yang terluka ke rumah sakit.
Kembali ke jalan di samping lapangan, kami memunguti kaleng gas air mata ke ember air. Suara tembakan semakin terdengar jelas. Kami bahkan dapat mendengar rentetan suara tembakan di ujung jalan Anwar al Mofti. Pecahan peluru berhamburan beberapa meter di samping saya. Kami bersembunyi di lorong mall. Kami tidak dapat kemanan-mana dan terkepung.
Kami segera sadar bahwa lorong mall itu terhubung dengan jalan masuk ke markas keamanan. Kami harus meninggalkan tempat itu segera, dan satu-satunya jalan adalah berlarian di ruang terbuka, yang diatasnya ada para penembak jitu.
Pada saat itu, dengan sisa tenaga baterai yang ada, aku menelpon ke saudaraku di Alexandria, “itu dimulai,”teriakku. Dia masih setengah mengantuk dan tidak begitu tahu apa yang saya katakan. “Lihat TV,” kembali teriakku.
Aku kemudian mencoba menelpon teman dekatku di London. Tidak diangkat. Aku mengirimkan pesan wasiatku lewat whatsapp, termasuk berapa jumlah hutang ke keluarga dan teman-temanku, selain juga mengirim beberapa informasi yang saya lihat sendiri selama pembantaian itu terjadi.
Waktu hampir habis dan hanya ada satu jalan keluar, walaupun beresiko.
Kami mencari tempat perlindungan di bawah tangga yang menghalangi kami dari penglihatan penembak jitu. Ada beberapa pemrotes yang ikut bergabung disana. Seorang pemuda di sampingku melangkah sejenak keluar gedung untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tidak menunggu lama, dia roboh tersungkur ke tanah.
Seketika, saya meloncat dan menariknya. Dia tertembak di lehernya. Darah mengucur deras di sekitar lehernya. Rupanya peluru itu melukai lehernya, hanya saja dia masih sadar.
Prioritasku adalah menjaganya dan orang-orang yang terluka. Seseorang pria berkaos T-shirt memerbannya untuk menghentikan lukanya.
Kami harus bertindak cepat untuk mengeluarkan korban yang terluka. Lelaki yang tertembak di lehernya dipanggul oleh beberapa orang termasuk Saleh, sembari menunggu suara tembakan terhenti.
“Sekarang”, salah dari mereka berteriak dan kemudian mereka berlarian di sepanjang lorong menuju tempat lain disebelahnya. Tidak lama, kami menyusul mereka bersama Amr.
Aku sepertinya tidak banyak berpikir. Pikiranku buntu. Tanpa banyak bicara, kami hanya menghela nafas dalam-dalam dan kemudian berlari secepatnya.
Ketika sedang berlarian, kembali rentetan senjata menggema, dadaku terasa sesak dan kemudian aku terjatuh. Aku tidak bisa bernafas, darah keluar dari mulutku. Rupanya gas air mata telah masuk ke paru-paruku.
“Aku tidak bisa bergerak,” kataku kepada Amr. “Aku tidak bisa bernafas.”
Namun Amr menyemangatiku, “Kita tidak bisa tetap disini, kita harus pergi,” ujarnya.
Dia mengangkatku sambil menghadapkannya ke tembok serta menaruh inhaler asma ke mulutku seraya berkata, “Hirup”. Setelah dua sedotan, dadaku terasa lebih ringan dan dapat bernafas normal lagi. “Ayo pergi.”
Kami bergegas menuju rumah sakit yang dapat ditempuh melewati beberapa rute yang tidak terlalu jauh.
Ketika sampai di rute pertama, kami bertemu dengan seorang petugas keamanan yang memakai penutup muka hitam sambil membawa senjata berjalan beberapa meter menuju kami dari arah samping. Kami sempat bertatap mata, sebelum kemudian dia kembali ke arah samping jalan dan menghilang.
Segera kami kembali ke jalan semula, ketika sekelompok pengunjuk rasa berlarian menuju kami, sambil berteriak, “Kembali. Pasukan keamanan datang, kembali.” Kami terkepung dan terjebak.
Kami berlarian ke blok apartemen dan mencoba membuka pintu untuk mencari perlindungan. Namun pintu terkunci. Pikiran yang ada pada waktu itu adalah; ditahan atau mati.
Kami terduduk, menyerah, duduk di depan blok dengan perlindungan yang seadanya, pasrah menunggu apa yang terjadi.
Aku meneliti saku celanaku dan kemudian lega karena aku ingat masih membawa paspor, sehingga jika ada sesuatu yang terjadi maka akan mudah mengenaliku.Telpon selulerku mati dan tidak tahu dimana Saleh sekarang.
Tiba-tiba pintu blok apartemen di seberang terbuka. “Masuk”, teriak seorang lak-laki.
Kami semua berlarian menuju lelaki itu, didalam, kami bertemu dengan puluhan orang, beberapa diantaranya terluka. Belum cukup aman pikirku. Kami naik lagi ke lantai lima, menemukan gudang kosong, yang berukuran dua meter persegi, kami berenam masuk kedalam dan menutup pintunya.
Tidak ada cahaya, tidak ada sinyal telepon dan hanya ada jendela kecil. Kami masih mendengar rentetan tembakan yang tidak berhenti dari seberang jalan. Sirene meraung-raung. Kami juga mendengar helikopter terbang rendah di lapangan, dan suara pengeras suara di tengah lapangan. Kami sepenuhnya menyadari bahwa kapanpun tentara dapat menemukan dan membunuh kami semua. Kami tidak banyak bicara karena perasaan takut yang menyergap.
Satu jam berlalu. kami memutuskan memeriksa keadaan di luar. Ada sinyal telepon di luar. Amr segera menghidupkan internetnya dan baru tahu jika telah ada 300 orang yang meninggal dalam serbuan tentara pagi ini. Hari telah menjelang siang.
Salah satu pendemo yang bersama kami memanggil temannya yang tinggal di disana. Dia bergegas ke atas flat. Seseorang membuka pintu dan menekan telunjuknya ke bibir minta kami tenang.
Didalam, ternyata telah ada lebih dari 40 orang yang bersembunyi. Suasananya senyap, korden ditutup, tidak ada listrik, satu-satunya yang aku dengar adalah suara kacau balau di luar. Ada anak-anak, orang tua, dan wanita di dalamnya. Orang yang membuka pintu meminta telponku dan kemudian menyuruh kami menuju ke ruang tamu.
“Bagaimana keadaan disana?”, tanya salah seorang berbisik sesaat saya duduk di lantai. “Apakah mereka telah membersihkan tenda-tenda atau kita masih bertahan?”
Saya diam tidak menjawab.
Beberapa orang yang duduk di lantai terkena tembakan senjata, sementara yang lain masih tampak kesakitan karena terkena gas air mata. Beberapa orang merawat yang terluka dengan obat seadanya. Tuan rumah masuk dari ruang ke ruang untuk membantu beberapa korban yang luka.
Kami masih tidak tahu keadaan Saleh. Kami masih mendengar suara gaduh di lapangan Rabaa; artinya pasukan keamanan belum berhasil membersihkan lapangan dari para pengunjuk rasa dan masih menangkapi kami.
Pada pukul 6 sore, ledakan besar mengguncang gedung, suasana menjadi sunyi. Kami tahu mereka sudah berhasil membersihkan lapangan.
Aku kekelahan dan tertidur. ketika malam tiba, suara tembakan sudah mulai memudar. Tidak ada lagi terdengar suara sirene maupun helikopter.
Pada pukul 5 pagi, kami semua terbangun oleh salah seorang pengunjuk rasa yang memberitahukan keadaan terbaru.
Dia bilang bahwa aksi protes sudah dibersihkan dan jam malam diberlakukan dan akan berakhir pukul 7 pagi. Jumlah pasukan keamanan yang berjaga mulai berkurang dan tampaknya cukup aman untuk pergi.
Dia menasehati kami semua untuk memotong janggut karena polisi di jalanan menyasar para pria yang dicurigai ikut dalam aksi protes kemarin.
Sesegera keluar dari gedung, aku mencium bau terbakar. Tampak para petugas kebersihan sedang bekerja mengumpulkan sampah dan tenda di lapangan.
Orang tua berdiri di samping gedung mendekatiku dan bertanya, “Apa kamu perlu sesuatu?, tanyanya.
Aku meminta sepatu, sesaat dia tersenyum dan membuka tas hitamnya untuk memberiku sepatu.
Kami kembali ke tempat tenda kami dulu didirikan. terlihat darah berceceran. Sepatu dan pakaian berserakan di jalan. Dan juga banyak longsongan peluru.
Disana pula, saya menemukan tenda, pakaian dan beberapa kartu akses kereta bawah tanah , kartu mahasiswa dan kunci flat di London. Namun, semuanya saya buang.
Kami menelpon Saleh untuk memastikan apakah dia selamat. Kami menunggu di apartemen tempat kami menginap selama dalam perjalanan di Kairo. Di apartemen itu pula, kami baru tahu jika salah satu teman kami, Ahmed Sonbol meninggal dalam kejadian itu dalam usia muda, 24 tahun. Dia adalah asisten dosen di Universitas Amerika, Kairo meninggal ketika membantu korban luka di rumah sakit lapangan. Pertemuan dengan Saleh menjadi peristiwa yang mengharukan. Dalam 15 jam peristiwa pembubaran demonstrasi di siang bolong, ternyata telah merenggut nyawa ratusan orang.
Selama proses pemakaman, kami tidak dapat ikut serta. Kami hanya terdiam seharian di flat, belum bisa memahami apa yang baru saja terjadi.
Di sore harinya, kami baru keluar ke masjid yang dijadikan sebagai kamar jenazah sementara, setelah sebelumnya masjid di Rabaa dibakar aparat keamanan selama pembubaran aksi protes.
Sesaat aku menginjakkan kaki ke dalam masjid Al Iman, bau menyengat menyerang tenggerokanku, antara campuran darah dan keringat, seperti bau terbakar.
Di lantai, dari pintu masuk masjid, ada banyak berjejer jenazah yang terbungkus dengan kain kafan.
Nama-nama jenazah di tempel di pintu masuk agar dikenali keluarga tercintanya. Ada beberapa wanita yang duduk dekat dengan jenazah anak dan suaminya.
Beberapa orang tampak menangis setelah mengenali orang-orang yang terbungkus kain kafan itu. Ada keheningan sesaat, namun kemudian goncangan tangis atas kepergian orang-orang yang dicintainya.
Ada peristiwa yang tampak mengundang banyak perhatian para juru foto dan jurnalis. Ketika aku mendekat, bau terbakar menyengat hidungku. Terdapat dua balok besar di taruh diatas jenazah.
Salah seorang dokter menarik kain kafan yang menutupi salah satu bagian tubuhnya atau tepatnya apa yang tersisa. Bagian kepala menghitam, dan sebagian tengkoraknya telah hilang. Butuh beberapa waktu untuk menyadarinya bahwa orang-orang ini telah dibakar hidup-hidup.
Hingga saat ini, tak seorangpun diseret karena bertanggung jawab atas tragedi Rabaa, bahkan yang terjadi, orang yang memerintahkan aksi brutal itu, Jenderal Abdel Fatah al Sisi kini menjabat presiden Mesir.
Kami melihat itu dengan penuh keheranan ketika dua tahun kemudian, David Cameron menggelar karpet mereka di London untuk rejim yang bertanggung jawab atas kematian teman-teman kami dan ribuan lainnya, bahkan warga negara Inggris sendiri, kamerawan Sky News, Mick Deane.
Debu itu masih terasa di Rabaa, masyarakat Mesir terpecah semakin dalam, lebih dalam yang ketimbang yang kami bayangkan. Kami melihat teman, sahabat, keluarga dan para aktivis yang menyebut diri mereka sebagai pembela HAM bersuka cita atas pembantaian, seolah darah yang tertumpah di mata mereka tidak berarti apapun.
Ini adalah kenyataan yang menyedihkan. Mereka menuduh kami menjadi anggota Ikhwanul Muslimin. Mereka gagal menyadari bahwa orang-orang dari pelbagai latar belakang berkumpul di Rabaa untuk menentang kudeta.
Meskipun penderitaan yang aku alami, selalu ada kebaikan: dua hari setelah pembantaian, seseorang mengirimiku pesan harapan, dan satu setengah tahun kemudian, orang itu menjadi isteriku. Bagi kami, 14 Agustus akan kami ingat sebagai hari peringatan atas kesempatan hidup keduaku.
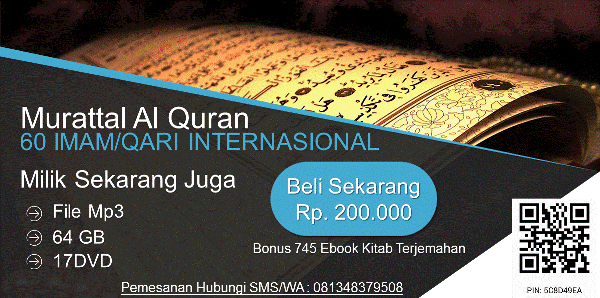
















0 komentar:
Post a Comment