KITA tak hanya harus belajar dari kemenangan dan keberhasilan. Kadang kita perlu belajar juga dari kekalahan. Karena dengan demikian kita akan memahami hal-hal yang menjadi penyebab kekalahan itu dan dapat menghindarinya pada masa-masa yang akan datang. Itulah di antara alasan mengapa kita mempelajari Sejarah.
Pada awal Ramadhan tahun 114 H (732 M), telah terjadi salah satu pertempuran yang paling menentukan sepanjang sejarah. Pertempuran itu terjadi di suatu tempat di Prancis, di antara kota Tours dan Poitiers, dan kemudian dikenal sebagai Balat al-Syuhada, pavements of martyrs. Paul K. Davis memasukkan peristiwa ini dalam daftar 100 Decisive Battles-nya. Sementara seorang penulis lain, Edward Creasy, memasukkan pertempuran ini dalam bukunya, Fifteen Decisive Battles of the World.
Kapan dikatakan sebuah pertempuran bersifat menentukan jalannya sejarah? Menurut Paul K. Davies (1999: xi), sebuah pertempuran dikatakan ’menentukan’ ketika memenuhi salah satu dari tiga kriteria berikut ini.
Pertama, pertempuran itu berdampak pada perubahan sosial politik yang sangat penting (brought about a major political or social change).
Kedua, sekiranya hasil dari pertempuran itu berbeda 180 derajat, maka akan terjadi perubahan besar-besaran secara politik dan sosial (had the outcome ... been reversed, major political or social changes would have ensued).
Ketiga, pertempuran tersebut menandai dimulainya perubahan penting dalam strategi perang (marks the introduction of a major change in warfare). Pertempuran yang tengah kita bicarakan ini, termasuk dalam kategori yang kedua.
Balat al-Syuhada, dalam sejarah juga dikenal sebagai Pertempuran Tours atau Pertempuran Poitiers, terjadi antara pasukan Muslim dari Andalusia yang dipimpin oleh Abdul Rahman al-Ghafiqi melawan pasukan Perancis yang dipimpin oleh Charles Martel. Pada pertempuran ini kaum Muslimin kalah dan Abdul Rahman sendiri turut gugur sebagai syuhada.
Muhammad Abdullah Enan dalam bukunya Decisive Moments in the History of Islam (1983: 43) menyebutkan betapa para ahli sejarah, terutama di Barat, berandai-andai bahwa sekiranya hasil dari pertempuran ini berbeda 180 derajat, yaitu kaum Muslimin menang dan pasukan Perancis kalah, maka ‘tidak akan ada lagi Eropa yang Kristen atau agama Kristen, dan Islam akan mendominasi Eropa.’
Ia juga mengutip pendapat Edward Gibbon yang mengatakan bahwa pada titik itu (di daerah antara Poitiers dan Tours, pen.) garis kemenangan kaum Muslimin telah mencapai 1000 mil ke Utara dihitung dari Gibraltar. Sekiranya mereka mampu meneruskan jarak kemenangannya dengan jumlah yang sama, maka mereka akan mampu mencapai Polandia dan Dataran Tinggi Skotlandia. Jika itu benar-benar terjadi, ‘barangkali tafsir al-Qur’an pada masa sekarang ini akan diajarkan di sekolah-sekolah Oxford, dan mimbar-mimbarnya mungkin menunjukkan pada orang yang bersunat akan kesucian dan kebenaran Wahyu Muhammad’ (1983: 48). Kemungkinan-kemungkinan inilah yang membuat para sejarawan memandang pertempuran ini sebagai decisive battle.
Enan sendiri dalam pengantar bukunya (1983: iv) memandang pertempuran ini sebagai salah satu dari dua pertempuran paling menentukan antara Islam dan Barat (the greatest decisive encounters of Islam and Christendom). Pertempuran yang satunya lagi adalah pengepungan Konstantinopel yang telah dimulai sejak 32 H (653 M). Kegagalan kaum Muslimin dalam dua pertempuran tersebut telah menunda, atau menghalangi, penetrasi Islam ke Eropa, masing-masing dari pintu masuk Timur dan Barat-nya.
Bagaimana jalannya Pertempuran Tours atau Poitiers ini sendiri? Dan apa yang menyebabkan kekalahan kaum Muslimin pada pertempuran tersebut? Kita akan melihatnya lebih jauh.
Pertempuran ini terjadi sekitar 20 tahun setelah masuknya Islam ke Andalusia di bawah kepemimpinan Tariq ibn Ziyad dan Musa ibn Nusayr. Sejak awal sudah tampak keinginan para pemimpin Muslim ini untuk membuka lebih jauh wilayah Eropa. Musa ibn Nusayr dan Tariq ibn Ziyad sudah menyeberangi Pegunungan Pyrenees yang membatasi wilayah Spanyol dan Perancis untuk memasuki wilayah yang terakhir ini lebih jauh lagi dan, tidak tertutup kemungkinan, untuk mencapai Konstantinopel dari arah Barat (Eropa).
Namun ketika kedua tokoh ini baru menguasai beberapa bagian Selatan Perancis mereka dipanggil menghadap Khalifah di Damaskus. Sepeninggal Musa ibn Nusayr hingga ke masa Abdul Rahman al-Ghafiqi setidaknya ada lima orang lainnya yang ditunjuk oleh Damaskus untuk memimpin Andalusia (Reinaud, 1964). Sejak memasuki Andalusia, kekuatan kaum Muslimin terus merambah wilayah Selatan, Tengah, dan bahkan Utara Perancis (Davis, 1999: 103). Namun, laju penetrasi pasukan Muslim ke Perancis berjalan relatif lambat disebabkan ketidakstabilan politik di Andalusia pada masa itu.
Keadaan sosial dan politik menjadi lebih baik saat Abdul Rahman al-Ghafiqi ditunjuk untuk memimpin Andalusia. Kepemimpinannya yang baik dan adil membuatnya disukai oleh orang-orang yang dipimpinnya. Dalam membagikan pampasan perang, ia terbiasa mendahulukan kepentingan anggota pasukannya daripada kepentingannya sendiri. Ia juga merupakan seorang pemimpin yang saleh dan dikenal sebagai salah seorang sahabat Ibn Umar radhiyallahu ’anhu, salah seorang Sahabat Rasulullah shallallhu ’alaihi wasallam (Reinaud, 1964: 43; Alatas: 2007: 151).
Enan (1983: 45) menjelaskan bahwa al-Ghafiqi merupakan pemimpin dan administrator yang tangguh, seorang pembaharu yang antusias, seorang yang memiliki kebaikan dan kualitas yang ideal, serta memiliki rasa keadilan, kesabaran, dan relijiusitas yang tinggi. Secara umum Enan melihat sosok al-Ghafiqi sebagai pemimpin (Wali) Andalusia yang terbesar dan paling handal. Sejak era kepemimpinannya, menurut Reinaud (1964: 44), gubernur-gubernur yang tidak amanah diganti dengan orang-orang yang jujur. Orang-orang Islam dan Kristen diperlakukan secara adil, sesuai dengan perjanjian yang terjalin di antara mereka. Gereja-gereja yang dirobohkan secara semena-mena diperbaiki kembali. Demikian juga sebaliknya, gereja yang dibangun dengan cara korupsi, yaitu dengan cara menyogok penguasa setempat, diperintahkan untuk dirobohkan.
Al-Ghafiqi sangat waspada terhadap potensi konflik internal dan pemberontakan di Andalusia serta terhadap kemungkinan ancaman dari arah Utara. Oleh karena itu, ia segera mengirim pasukannya ke Utara, menyeberangi pegunungan Pyrenees, untuk memerangi salah satu gubernurnya di Perancis Selatan, Uthman ibn Abi Nis’ah, yang menentang kepemimpinannya dan bersekutu dengan penguasa Kristen di wilayah itu, yaitu Eudo, Duke of Acquitaine. Pasukan yang dikirim al-Ghafiqi berhasil menumpas perlawanan Ibn Abi Nis’ah. Al-ghafiqi sendiri kemudian menyusul ke Utara dengan pasukan yang kuat untuk menghadapi ancaman Duke Eudo dan pasukannya.
Al-Ghafiqi memasuki wilayah Perancis pada musim semi 732 M (awal 114 H), kurang lebih satu tahun setelah ia diangkat menjadi Wali Andalusia. Satu persatu wilayah Acquitaine berhasil diduduki pasukannya. Eudo berusaha menahan pasukan al-Ghafiqi di tepi Sungai Dordogne. Namun dalam pertempuran ini Eudo menderita kekalahan telak dan banyak anggota pasukannya yang mati di pertempuran itu. Al-Ghafiqi mengejar Eudo hingga ke ibukota kerajaannya di Burdal, Bordeaux, yang segera takluk ke tangannya setelah pengepungan singkat. Seluruh Acquitaine kemudian jatuh ke tangan Muslim. Sementara Eudo sendiri melarikan diri ke Utara, pasukan Muslim mulai memasuki wilayah Burgundi dan menaklukkan kota-kota seperti Lyon dan Besancon. Sebagian pasukan Muslim bahkan berhasil mencapai Sens yang terletak hanya seratus mil saja dari Paris. Pasukan al-Ghafiqi kemudian bergerak ke arah Barat hingga ke tepi Sungai Loire. Dari sana mereka bersiap untuk ke Utara menuju pusat Kerajaan Frank (Perancis) (Enan, 1983: 47-8).
Kerajaan Frank ketika itu dalam masa transisi antara Dinasti Merovingian dan Dinasti Carolingian. Walaupun secara resmi masih dipimpin oleh seorang raja Merovingian yang sudah tak lagi memiliki kekuasaan riil, Kerajaan Frank ketika itu secara efektif dikendalikan oleh Charles Martel. Kerajaan Frank pada masa itu, dan pada abad-abad setelahnya, dapat dikatakan sebagai kerajaan terkuat di Eropa Barat dan merupakan sekutu paling setia dari kepausan Katholik di Roma. Melihat gerakan pasukan Islam yang semakin berbahaya, Charles Martel menghimpun pasukannya. Eudo sendiri, yang merupakan saingan Charles Martel dan selama sekian lama berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat, kemudian datang dan meminta bantuan pada Charles Martel. Charles menyetujuinya denga syarat Eudo akan terus loyal kepadanya.
Sementara itu, Pasukan Muslim telah mencapai daerah di antara Poitiers dan Tours. Mereka menyerang dan menguasai kedua kota itu. Tak lama setelah itu, di wilayah antara Poitiers dan Tours, pasukan Muslim mulai berhadapan dengan pasukan Frank yang dipimpin oleh Charles Martel. Laporan tentang jumlah pasukan Muslim beragam, antara 20.000 sampai 80.000. Sementara jumlah pasukan Frank dilaporkan secara beragam juga, ada yang menyatakan lebih sedikit dari pasukan Muslim dan ada yang yang menyebutkan angka yang lebih besar. Pasukan Frank kebanyakannya merupakan pasukan irregular, nyaris telanjang, dengan rambut ikal yang tergerai hingga ke bahu, serta mengenakan kulit serigala.
Pasukan yang dibawa al-Ghafiqi ketika itu merupakan pasukan terkuat dan terbesar yang pernah dibawa ke Perancis. Namun jumlah pasukan sudah agak berkurang setelah melalui berbagai pertempuran. Pada saat itu mereka juga menghadapi ujian yang cukup serius: harta! Sepanjang penaklukkan berbagai kota di Perancis, pasukan Muslim berhasil mengumpulkan banyak pampasan perang. Harta itu bisa menjadi kekuatan ekonomi bagi Muslim selepas perang. Tapi masalahnya perang belum selesai. Dan kini mereka justru sedang dihadapkan dengan kekuatan inti lawan.
Al-Ghafiqi mulai mengkhawatirkan keberadaan pampasan perang yang ada di tangan pasukannya. Ia khawatir perhatian pasukannya terpecah antara menghadapi musuh dengan menjaga pampasan perang agar tidak jatuh ke tangan musuh. Ia meminta agar sebagian pampasan perang itu ditinggalkan saja, tapi ia tidak mampu memaksakan hal ini karena khawatir anggota pasukan akan menentangnya di saat yang cukup genting tersebut.
Kedua pasukan tidak langsung bertempur. Mereka saling mengawasi selama kurang lebih seminggu. Kesempatan ini digunakan oleh pasukan Muslim untuk mengamankan harta yang telah mereka kumpulkan agak jauh ke Selatan. Akhirnya pertempuran bermula pada tanggal 12 atau 13 Oktober 732 (akhir Sha’ban 114). Selama tujuh hingga delapan hari berikutnya kedua pasukan terlibat dalam pertempuran kecil. Kemudian pada hari kesembilan mereka memasuki pertempuran besar yang melibatkan seluruh anggota pasukan. Mereka bertempur hingga malam hari tanpa ada pihak yang menang.
Pada hari kesepuluh kedua belah pihak saling menyerang lebih keras lagi. Kubu Perancis memperlihatkan strategi pertahanan yang kokoh dan menyulitkan kaum Muslimin untuk menyerang. Enan menyebutkan bahwa pasukan Perancis pada akhirnya mulai kelelahan dan tanda-tanda kemenangan mulai berpihak kepada pasukan Muslim. Tapi sayangnya banyak di antara anggota pasukan Muslim yang terlalu khawatir akan jatuhnya pampasan perang ke tangan musuh. Sehingga ketika mereka mendengar seruan dari tempat penjagaan harta bahwa musuh mulai melakukan penetrasi ke tempat itu, konsentrasi pasukan Muslim menjadi terpecah. Banyak di antara mereka yang meninggalkan tempatnya dan menuju tempat harta pampasan perang berada. Hal ini menimbulkan kekacauan di dalam barisan Muslim dan membuka peluang bagi musuh.
Al-Ghafiqi berusaha untuk mengembalikan pasukannya pada posisi mereka semula. Tapi semuanya sudah terlambat. Dalam keadaan yang tidak menentu itu, ia terkena anak panah yang dilontarkan musuh. Ia terjatuh dari kudanya dan mati syahid. Keadaan menjadi semakin kacau dan musuh berhasil mendesak pasukan Muslim. Walaupun mendapat pukulan bertubi-tubi dan banyak korban yang gugur, kaum Muslimin masih bisa mempertahankan posisi mereka hingga pertempuran dihentikan pada hari itu. Kedua belah pihak kembali ke posisi masing-masing dan bersiap-siap menyongsong pertempuran baru keesokan harinya. Namun pasukan Muslim tidak bersiap untuk menyongsong pertempuran baru. Mereka menyadari bahwa mereka sudah kalah dan pemimpin mereka sudah gugur. Maka secara diam-diam mereka memutuskan untuk mundur pada malam harinya dan meninggalkan semua pampasan perang yang sejak awal berusaha mereka jaga.
Keesokan paginya pasukan Frank merasa heran dengan kesunyian di kubu Muslim. Mereka kemudian menyadari bahwa lawan mereka sudah pergi meninggalkan pertempuran. Charles Martel dan pasukannya merasa cukup dengan hasil pertempuran itu dan tidak merasa perlu untuk mengejar pasukan Muslim. Mereka mengambil harta pampasan perang yang ditinggalkan pasukan Muslim dan kemudian kembali pulang (Enan, 1983: 56-9; Davis, 1999: 104-6).
Peristiwa itu kemudian dikenal dalam Sejarah Islam sebagai Balat al-Syuhada’ atau Dataran Syuhada. Para Sejarawan hanya bisa berandai-andai atas apa yang akan terjadi sekiranya pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan Muslim. Bagaimana keadaan Eropa setelah itu sekiranya Kerajaan Frank dan seluruh wilayah Perancis jatuh ke tangan Muslim? Akankah Paris, dan mungkin juga setelah itu London, dan berbagai kota penting Eropa lainnya, menjadi pusat-pusat kebudayaan Islam?
Tapi kita tidak perlu berandai-andai. Semuanya sudah ditetapkan Allah dan ketetapan Allah adalah yang terbaik. Kita hanya perlu belajar dari Sejarah, bahwa adakalanya bukan musuh yang kuat yang mampu menaklukkan dan mengalahkan kita. Kita hanya perlu belajar bahwa adakalanya, atau malah seringkali, yang membuat kita takluk dan kalah justru ketidakmampuan kita sendiri dalam mengontrol hawa nafsu yang bersumber pada kecintaan yang berlebihan terhadap harta duniawi. Wallahu a’lam bis showab.
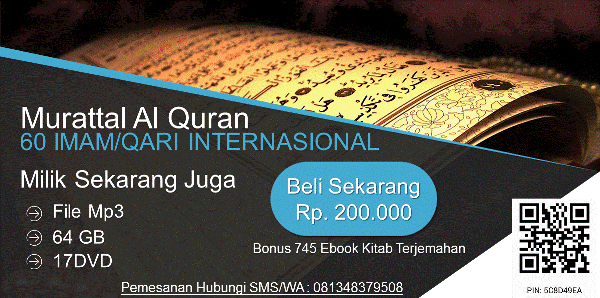


0 komentar:
Post a Comment