Tuanku Imam Bondjol adalah pahlawan nasional Indonesia abad kesembilan belas awal, yang sering dianggap Wahabi, pemimpin paling terkenal Perang Padri. Dalam sejarahnya, Perang Padri bisa dianggap sebagai awal munculnya ancaman kelompok Islam di Asia Tenggara. Fenomena ini diawali dari kembalinya orang-orang yang pulang dari menunaikan ibadah haji di Makkah.
Di bawah pengaruh pemikiran Wahabi, mereka mencoba untuk memurnikan penerapan ajaran Islam di Sumatera, yang berujung pada terjadinya konflik kekerasan dengan masyarakat lokal Muslim (kaum adat) dan penjajah Belanda pada tahun 1830-an.
Selama beberapa dekade nama Tuanku Imam Bonjol, ulama, Pejuang Perang Padri hadir di ruang publik bangsa: sebagai nama jalan, nama stadion, nama universitas, bahkan di lembaran Rp 5.000 keluaran Bank Indonesia 6 November 2001. Tuanku Imam Bonjol (1722-1864), diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI Nomor 087/TK/Tahun 1973, 6 November 1973.
Setelah peristiwa 11 September di AS, ada beberapa perdebatan seputar Padri dan Imam Bondjol yang memakai sorban dan berjenggot panjang. Ada yang menggugat kenapa Indonesia memasukkan “teroris” Islam sebagai pahlawan dan bahkan gambarnya dicetak dalam uang kertas lima ribu rupiah oleh Bank Indonesia. Namum secara umum para ahli sejarah Indonesia tidak mempermasalahkan hal itu, karena proklamator Indonesia sendiri, Soekarno dan Muhammad Hatta menyebut Imam Bonjol sebagai Pahlawan Indonesia.
Di Belanda pada 1928, Mohammad Hatta menyampaikan pidato berbahasa Belanda dengan tema “FreeIndonesia.” Dalam sambutannya, Hatta mengkritik kebijakan kolonial Belanda yang memaksa rakyatnya untuk mempelajari legenda heroik William Tell, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, William orange, dan lain-lain dan pada saat yang sama meremehkan tindakan Indonesia yang menentang Penjajahan Eropa:
“So too must Indonesian youth parrot its masters and call its own heroes, like Dipo Negoro, Toeankoe Imam, Tengkoe Oemar and many others, rebels, insurgents, scoundrels,and so on”
“Pemuda Indonesia juga dipaksa menjuluki pahlawan sendiri, seperti Diponegoro, Toeankoe Imam, Tengku Oemar dan banyak lainnya, sebagai pemberontak, pengacau, penjahat, dan sebagainya”.
Menariknya dalam terjemahan buku Muhammad Hatta pada 1972 kata scoundrels diterjemahkan dengan kata “teroris”, satu hal yang tidak mungkin digunakan untuk menerjemahkan kata itu hari ini.
Kondisi Minangkabau sendiri waktu itu penuh dengan kemerosotan moral di masyarakat. Hingga akhirnya terjadi upaya untuk melakukan perbaikan yang dipelopori para ulama Minangkabau yang baru pulang dari Makkah, yang kemudian disebut sebagai kaum Padri. Gerakan tersebut mendapatkan dukungan yang begitu besar dari masyarakat Minangkabau saat itu.
Hal itu terjadi karena reformasi yang digulirkan berhasil meningkatkan kemakmuran rakyat Minangkabau. Di samping itu, rakyat sudah lama kecewa dengan kepemimpinan para penghulu serta kemunduran perdagangan dan ekonomi Minangkabau. Christine Dobbin, seorang peneliti dari Australia dalam tulisannya “Economic Change In Minangkabau As A Factor In The Rise Of The Padri Movement, 1784-1830” mengakui kemajuan yang berhasil dicapai atas reformasi (yang lebih tepatnya disebut revolusi karena menyangkut berbagai aspek kehidupan walaupun yang paling tampak adalah praktik beragama, ekonomi dan politik) yang dipelopori oleh para ulama Minang ini.
Dalam konsep adat Minangkabau sendiri terdapat sistem dua laras: Koto Piliang dan Bodi Caniago. Koto Piliang lebih bersifat hirarkis, sedangkan Bodi Caniago lebih didasarkan pada prinsip network yang lebih egaliter, dimana nagari dipegang oleh sekelompok penghulu yang merepresentasikan suku-suku yang terpandang.
Tidak lama setelah terjadinya islamisasi pada abad ke-16, sistem pemerintahan di Minangkabau menganut tiga raja: Raja Alam (raja dunia), Raja Adat (raja hukum adat), dan Raja Ibadat (raja agama Islam). Ketiganya disebut sebagai Raja Tiga Selo.
Dalam realitasnya kerajaan tidak pernah berfungsi sebagai institusi pemerintahan di daerah inti (luhak), yaitu; Agam, Tanah datar, dan Lima Puluh Kota. Jantung Minangkabau yang disebut darat ini tidak diperintah oleh raja, tetapi oleh penghulu (kepala adat) dengan pola organisasi sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip genealogis. Daerah inilah yang menjadi basis gerakan Padri. Mereka tidak pernah berada dalam kontrol raja. Keluarga kerajaan hanya memerintah daerah rantau, daerah pinggiran pantai, yang didasarkan pada perspektif teritorial.
Selain itu, Minangkabau juga merupakan etnis yang menganut konsep matrilineal terbesar di dunia Islam. Konsep ini bertentangan dengan Islam yang menggunakan konsep patrilineal. Kondisi ini, ditambah dengan berbagai kerusakan moral, mulai dari maraknya candu, perjudian, sabung ayam, perampokan, pembegalan, hingga penculikan memicu lahirnya gerakan pembaruan yang berusaha melakukan perbaikan di masyarakat.
Usaha perbaikan ini diawali oleh Tuanku Nan Tuo pada 1784-1803 dengan menggunakan metode dakwah yang pada akhirnya terkadang tidak bisa dihindarkan dari benturan fisik. Usaha perbaikan ini kemudian memasuki babak baru yang diawali oleh kedatangan tiga orang haji dari Makkah, yaitu Haji Miskin, Haji Abdurrahman, dan Haji Muhammad Arif yang memilih pendekatan kekuatan dan kekuasaan dalam menerapkan Syariat Islam. Gerakan mereka ini kemudian dikenal sebagai Gerakan Padri.
Haji Miskin memandang bahwa perubahan secara menyeluruh pada masyarakat Minangkabau menuju masyarakat yang Islami bisa dicapai secara sah (syar’i) melalui penggunaan kekuatan. Merasa tidak puas dengan pola akomodatif yang dilakukan oleh Tuanku Nan Tuo. Haji Miskin menemukan partner yang tepat dalam diri Tuanku Nan Renceh, yang memiliki pandangan yang sama bahwa perubahan bisa dilakukan dengan penggunaan kekuatan.
Bukit Kamang, kampung Tuanku Nan Renceh, menjadi daerah basis bagi gerakan Padri untuk melakukan reformasi di masyarakat. Secara bertahap, Tuanku Nan Renceh mampu membangun aliansi yang kuat dengan tujuh ulama lainnya di Agam.
Jihad pun mulai dilakukan. Dalam proses jihad periode pertama, yang ditandai dengan perlawanan antara kaum Padri dan kaum Adat terjadi beberapa tindakan yang dianggap berlebihan. Namun mereka berhasil mendirikan daerah basis di Bonjol yang menjadi basis pemerintahan yang menjalankan Syariat dan membawa kemakmuran di Minangkabau.
Dalam periode kedua, merupakan kenyataan sejarah bahwa kaum Adat yang beragama Islam justru meminta bantuan kepada Belanda yang kafir, sesuatu yang sangat terlarang dalam Islam dan di kemudian hari akhirnya mereka sesali saat melihat kekejaman Belanda.
Pada periode ketiga, kaum Adat akhirnya bersekutu dengan kaum Padri untuk melawan penjajahan Belanda. Menghadapi persatuan dari rakyat Minangkabau, penjajah Belanda mengerahkan pasukan dari koalisi internasional yang didatangkan dari Jawa, Batavia, Bugis, Madura, Sepoy, Eropa, dan Afrika.
Pada akhirnya, kaum Padri bersama kaum adat kalah dari pasukan koalisi pimpinan Belanda. Tuanku Imam Bonjol diasingkan, namun beberapa pengikut Imam Bonjol meneruskan gerilya di beberapa nagari di Minangkabau, meskipun pada akhirnya mereka dapat ditaklukkan Belanda. Tuanku Imam Bonjol, dengan jalan jihad yang ditempuhnya dalam perjuangan melawan penjajah Belanda, pada akhirnya diangkat menjadi pahlawan nasional oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(Ringkasan Laporan Khusus Lembaga Kajian SYAMINA Edisi XVIII/ MARET-APRIL 2015)
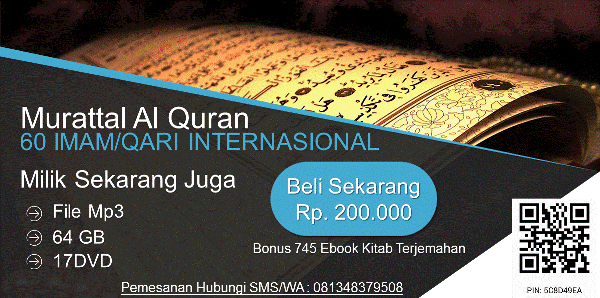


0 komentar:
Post a Comment